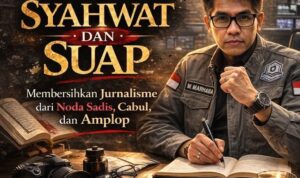Penulis: Belva Al Akhab dan Satrio
DETIKBABEL.COM, Mentok, Bangka Barat — Senja turun perlahan di Kampung Tanjung. Langit berwarna jingga menyelimuti deretan lapak sederhana yang dipenuhi kue bangkit, jongkong pandan, bingka labu, dan es buah berwarna-warni. Di antara aroma santan dan gula merah yang menguap dari kukusan, terdengar tawa yang tidak mempersoalkan identitas.
Di kota pelabuhan tua bernama Mentok, Ramadhan bukan hanya ibadah umat Islam. Ia adalah bahasa perjumpaan, ruang kebersamaan, dan perayaan kerukunan yang hidup dalam kebiasaan kecil: membeli takjil, menyapa tetangga, berbagi kue.
Bazar Ramadhan Kampung Tanjung, yang didukung oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, kembali dipadati warga dari berbagai latar agama pada Minggu sore (22/2/2026). Perempuan Melayu berkerudung berdiri berdampingan dengan warga Tionghoa yang memilih kue untuk berbuka tetangganya. Anak-anak berlari kecil membawa plastik takjil sambil tertawa, tanpa tahu bahwa mereka sedang mewarisi tradisi toleransi.
“Setiap Ramadhan saya selalu beli takjil di sini. Sudah jadi kebiasaan keluarga,” ujar Hendrawan, warga keturunan Tionghoa Mentok. Ia membeli beberapa bungkus kue bangkit untuk dibagikan ke tetangga Muslimnya.
“Kalau Imlek mereka kirim kami makanan juga. Kami saling jaga,” tambahnya pelan.
Di lapak kecilnya, Siti Aminah menyusun kue bangkit satu per satu seperti merangkai doa. Ia tersenyum melihat pembeli yang beragam.
“Di sini semua saling kenal. Kalau Natal atau Imlek kami ikut datang. Kalau Ramadhan mereka ikut beli takjil. Tidak pernah terasa berbeda,” katanya.
Kata-kata sederhana itu terdengar seperti puisi tentang Indonesia.
Mentok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah lama menjadi simpul pertemuan bangsa-bangsa. Sejak abad ke-18, pelaut Melayu, pedagang Tionghoa, saudagar Arab dan orang Eropa datang melalui pelabuhan timah. Dari transaksi ekonomi lahir hubungan sosial dari dapur rumah tangga tumbuh budaya berbagi.
Di pusat kota, masjid tua berdiri berdampingan dengan klenteng-klenteng bersejarah. Salah satu yang menjadi saksi perjalanan waktu adalah Masjid Jami Mentok, yang berdiri tak jauh dari rumah ibadah komunitas Tionghoa. Di halaman masjid, anak-anak belajar mengaji. Di jalan yang sama, warga Tionghoa menyalakan lilin sembahyang. Sejarah tidak mencatat konflik besar di antara mereka yang tercatat adalah kebiasaan saling menolong.
Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat menunjukkan komposisi masyarakat Mentok yang majemuk, dengan komunitas Melayu Muslim sebagai mayoritas dan komunitas Tionghoa yang signifikan. Sementara laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah dengan tingkat toleransi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun angka-angka itu menjadi nyata di Kampung Tanjung. Ia hidup dalam senyum penjual kue, dalam plastik takjil yang dibeli bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk tetangga.
Kerukunan di Mentok tidak diajarkan lewat pidato panjang. Ia lahir dari dapur.
Kue bangkit yang dipanggang dalam oven tua menyimpan teknik memasak Tionghoa. Santan, pandan dan gula merah membawa akar Melayu. Di atas loyang, sejarah bersatu tanpa pertengkaran.
Tokoh kuliner Indonesia William Wongso pernah menyebut makanan tradisional sebagai arsip budaya. Ia menyimpan jejak pertemuan manusia. Pemikiran itu terasa nyata di Mentok yaitu kue menjadi bahasa bersama.
Pedagang es buah bernama Firmansyah melihatnya setiap sore.
“Yang beli macam-macam. Ada yang pakai peci, ada yang pakai kalung salib, ada yang biasa saja. Semua senyum,” katanya.
Dalam bukunya Food Tourism Around the World, Erik Wolf menulis bahwa wisata kuliner mampu memperkuat identitas sekaligus kohesi sosial. Mentok adalah contoh kecil dari teori itu. Bazar Ramadhan menjadi panggung kebudayaan yang tidak direncanakan, tetapi diwariskan.
Julukan Mentok sebagai Kota 1.000 Kue bukan sekadar promosi wisata. Ia adalah metafora tentang keberagaman rasa dan manusia. Dari dapur Melayu hingga oven keluarga Tionghoa, kue menjadi jembatan sosial.
Program Pasar Ramadhan pemerintah daerah memang bertujuan menggerakkan UMKM. Namun secara sosial, ia menumbuhkan ruang perjumpaan. Orang datang membeli makanan, pulang membawa cerita.
Di tengah isu intoleransi di berbagai daerah Indonesia, Kampung Tanjung menghadirkan pemandangan berbeda. Harmoni yang lahir dari kebiasaan sehari-hari. Tidak ada slogan besar, tidak ada deklarasi megah. Hanya warga yang berbagi kue.
Menjelang azan magrib, kerumunan bubar perlahan. Jalanan kembali sepi. Tetapi di rumah-rumah kecil Mentok, plastik takjil dibuka bersama keluarga. Ada yang berbuka puasa, ada yang sekadar duduk menemani.
Di sanalah makna Ramadhan di Mentok
bukan hanya menahan lapar,
melainkan menjaga hati agar tetap hangat.
Bazar Ramadhan Kampung Tanjung adalah potret Indonesia dalam skala kecil. Di antara gula merah dan santan yang mengepul, kerukunan beragama menemukan bentuknya yang paling jujur.
Di kota pelabuhan tua ini, Ramadhan mengajarkan bahwa toleransi tidak lahir dari teori, tetapi dari kebiasaan saling berbagi. Dari kue bangkit yang dikirim saat Imlek. Dari takjil yang dibeli untuk tetangga. Dari senyum tanpa prasangka.
Mentok mengingatkan kita bahwa kerukunan bukan sekadar slogan negara, tetapi tradisi yang dijaga warga. Tradisi yang hidup dalam aroma dapur, dalam pasar sederhana, dalam hati manusia.
Ketika azan magrib berkumandang di langit Mentok, semua orang tahu
harmoni bukan hanya doa di masjid,
tetapi juga tangan yang saling memberi.